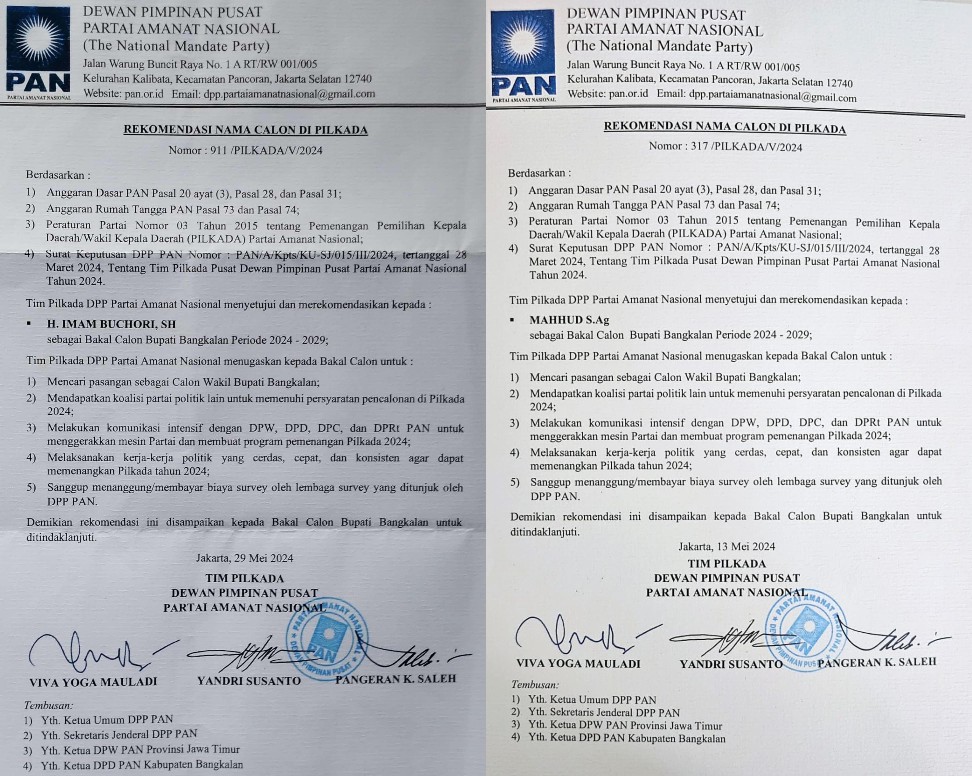Polemik Nasab Ba’alawi: Pertarungan Islam Historis Vs Islam Normatif

Barangkali kita harus jujur terlebih dahulu, tentang polemik nasab Ba’alawy yang tidak boleh dipisahkan dari dialektika realitas sosial, baik politik, ekonomi, budaya dan ragam aspek lainnya dalam kehidupan ini, dan rasanya yang paling dominan situasi itu merupakan efek dari menguatnya politik identitas dan polarisasi politik elektoral beberapa tahun yang lalu. Keadaan hari ini tidak selalu menyangkut data sejarah, karena itu penulis tidak tertarik membahas, mana yang lebih valid data sejarahnya antara dua kubu yang tengah bertikai. Penulis sendiri sangat percaya pada konsep Ibnu Khaldun (1332–1406 M) dalam Muqaddimah menyangkut narasi sejarah di permukaan (tarikh fi dhahirihi) dan analisis sejarah mendalam (tarikh fi bathinihi). Yang terakhir kemudian berkembang menjadi filsafat sejarah. Penulis dengan Kiai Imad sudah bertemu dan beberapa orang yang bertentangan dengannya.
Tahun 2019, saya sempat membuat tulisan berjudul Habaib Geneologis dan Habaib Metodologis, sebuah hasil refleksi dari realitas sosial-keagamaan dan politik di masyarakat Madura yang waktu itu dijumpai term, “Madura Bersama Habaib” yang bertebaran di jalan-jalan berupa spanduk berukuran besar. Tampaknya, posisi para habib populer sangat penting, magis dan sakral dalam sebagian masyarakat Madura, hingga hari ini, cosplay Habib Bahar bin Smith di jalan-jalan Madura sering terlihat.
Ada pertanyaan dalam diri: Bagaiaman jika orang-orang dalam Madura Bersama Habaib itu itu diperkenalkan dengan habib berdoktrin Syiah? Pertanyaan yang kemudian melahirkan konsep habaib geneologis dan habaib metodologis. Yang pertama, habib sebagai darah daging dan tulang Rasulullah yang secara normatif bagi sebagian kita memang harus dihormati, apapun latar belakang sejarah doktrin mereka. Yang kedua, habaib metodologis sebagai rujukan keislaman. Untuk yang kedua, kita boleh berbeda dan tidak harus bertemu, karena setiap orang punya pengalaman berbeda, pengalaman itu akan selalu mencari imamnya sendiri. Nah, yang fundamental dari Kiai Imad, ia mempersoalkan ketersambungan secara geneologis kalangan Ba’alawy yang merupakan asal usul habaib di Indonesia, kepada Rasulullah.
Awalnya penulis sulit percaya ketika pertama kali mendengar polemik menyangkut keterputusan nasab Ba’alawy di Indonesia kepada Rasulullah SAW, sebab polemik itu datang dari sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman al-Bantani, pendiri pesantren dan pengurus Nadhlatul Ulama, seorang penulis produktif, ahlusunnah tradisionalis, bukan akademisi murni di sebuah kampus yang bisa berpikir kritis kapan saja, bukan juga modernis dari Muhammadiyah atau PersIs, bukan juga salafi yang memang ingkar terhadap tradisi Ba’alawy, bukan juga dari al-Irsyad yang punya sejarah perseteruan dengan Ba’alawy di Indonesia dalam Jami’at Al-Khair, menyangkut konsep kafaah dalam pernikahan. Bagi Arab Ba’alawy, hukum pernikahan antara perempuan keturunan Rasulullah (syarifah) dengan laki-laki bukan keturunan Rasulullah, pernikahan keduanya batal, tidak sah. Sedangkan bagi Arab non-Ba’alawy, pernikahan itu sah, berdasarkan fatwa Syaikh Ahmad Surkati pendiri Jam’iyah al-Islah wa al-Irsyad. Fatwa yang kemudian menyebabkan Ahmad Surkati dikeluarkan dari Jami’atul al-Khair tahun 1914-M.
Kiai Imad datang dari ahlusunah wal jamaah tradisional di Indonesia, yang secara doktrin teologis terhimpun dalam madrasah Asy’ariyah-Maturidiyah, dengan tradisi fikih Syafi’i dan percaya kepada wacana akhlak-tasawuf yang dikembangkan oleh tokoh model al-Junaid, al-Ghazali dan yang lain. Sebuah doktrin yang sama dengan apa yang dipercaya dan dijalankan dalam lingkaran Ba’alawy.
Lantas apa yang menyebabkan pernyataan berdasarkan penelitian itu disampaiakan kepada publik oleh Kiai Imad? Sedangkan dalam Nahdlatul Ulama, tempat Kiai Imad berkiprah juga terdapat banyak kalangan habaib dari Ba’alawy. Pertanyaan yang kemudian menuntun penulis beberapa bulan lalu berkunjung kepada Kiai Imad di pesantrennya. Ketika itu, Kiai Imad mengaku sudah banyak yang memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikannya, tapi sifatnya bukan data sejarah yang menggagalkan tesisnya, tapi berupa ancaman bagi orang-orang yang tidak memuliakan keturunan Rasulullah. Apa yang telah dikemukakan, menurutnya bukan sesuatu yang baru, di Timur Tengah sudah banyak yang lebih dahulu mempertanyakan keabsahan nasab Ba’alawy.
Penulis terus berusaha memperdalam, tentang gejala apa yang melatarbelakangi pernyataan Kiai Imad. Ia lantas lebih banyak menyampaikan persoalan situasi keilmuan, bagaimana ada orang-orang dari kalangan Ba’alawy yang tidak punya kapasitas secara keilmuan keislaman tapi memperoleh panggung keagamaan, dan mereka dianggap pemilik otoritas keagamaan paling tinggi dan paling kuat sebab membawa-bawa cap sebagai keturunan Rasulullah. Menurutnya, geneologi itu (nasb) perlu dibuktikan terlebih dahulu validitasnya.
Penulis kemudian menangkap adanya gejala pertarungan antara tradisi Islam normatif (normative Islam) yang diwakili oleh pendukung nasab Ba’alawy tanpa argumentasi, dan tradisi Islam sejarah (historical Islam) yang sedang dijalankan oleh Kiai Imad, atau orang yang datang membantahnya dengan argumentasi. Islam normatif sebagai ketentuan menyangkut baik dan buruk, norma yang mutlak dan sakral, membatasi perilaku suatu masyarakat. Sedangkan Islam sejarah sebagai realitas sosial, politik, ekonomi hingga budaya. Dua terminologi yang digagas oleh Fazlur Rahman atau mungkin Ali Syari’ati dengan konsep teks dan konteks (text and context). Ilmuan Indonesia bernama A. Mukti Ali memperkenalkan keduanya dengan istilah dogmatis-ilmiah (scientific cumdoctrinaire). Unsur pertama dari terminologi yang terakhir ini membuat kajian Islam menjadi ilmiah. Kiai Imad dan orang-orang yang membatahnya dengan argumentasi dan membawa anti-tesis dari rumahnya mengajak kepada tradisi itu, yang tampak lebih sehat bagi dunia keislaman khususnya di Indonesia. Sebab Islam sebagai norma dan dogma sudah sangat kokoh dan pesat. Yang diingat dari perkataan Kiai Imad sebelum penulis meninggalkan kediamaannya; yang saya pertanyakan secara ilmiah, bukan secara hakikat, dan itu akan banyak manfaatnya kelak bagi kalangan Ba’alawy.